Detik-detik
Aku
berdiri di tengah tanah lapang dengan matahari nangkring tepat di atas kepala.
Luas tanah ini mungkin bisa membuat satu lapangan sepak bola dengan puluhan
ribu kursi untuk para suporter lengkap dengan tempat parkir yang luas untuk
memarkir kuda beroda milik para pendu-kung klub kesayangan mereka. Di sini aku
tidak sendirian, satu kawanku berdiri kira-kira dua meter di sebelahku. Aku dan
satu kawanku. Aku dan hanya satu-satunya kawanku. Jika saja aku bercerita lebih
awal, beberapa hari silam misalnya, aku tidak akan mengatakan dua kalimat
ter-akhir sebelum kalimat ini. Beberapa hari silam ratusan kawanku hidup nyaman
dan damai di sini. Beberapa hari silam juga terjadi pembantaian besar-besaran
oleh orang-orang tak dikenal kepada para kolegaku yang terjadi selama beberapa
hari sampai terakhir satu hari yang lalu. Dengan amat sangat aku berharap
kejadian pembantaian ini menjadi berita utama di halaman pertama koran hari ini
agar satu dunia tahu betapa kejinya mereka. Entah apa motif pembunuhan itu,
tapi yang pasti, aku dan satu kawanku selamat sampai saat ini.
Sebuah
tiang yang puncaknya terdapat reklame besar berdiri mantap di ujung tanah
lapang. Papan besar itu berisi gambar gedung tinggi yang sedang berbaris serta
terdapat tulisan yang tidak bisa kubaca karena memang aku tidak bisa membaca,
tidak pernah belajar membaca, apalagi mengenyam bangku sekolah. Perhatianku
teralihkan dari semula memperhatikan tulisan di reklame yang tidak bisa kubaca,
kini menjadi memperhatikan mobil hitam di ujung tanah lapang sedang bergerak
menuju ke arahku. Tidak kalah menarik perhatian, mobil yang ukurannya lebih
besar dari mobil hitam bergerak di belakangnya dan mengarah ke arah sama.
Delapan ban mulai melintasi permukaan tanah dan saking cepatnya ban-ban itu
bergulir, butiran-butiran tanah yang dilindas terusir dari tempatnya, terangkat,
lalu terbang dan menimbulkan efek seperti asap.
Prediksiku bahwa kedua kuda
beroda itu akan menabrakku dan satu kawanku sampai akhirnya kami tewas
mengenaskan di tempat ternyata salah. Mereka berhenti beberapa puluh meter dari
tempatku berdiri.
Empat
pasang kaki turun dari mobil hitam. Tiga orang pria dan satu wanita berambut
sebahu. Mereka terlihat asing bagiku, bukan mereka yang membunuh para kolegaku.
Aku belum pernah melihat mereka sama sekali dan pastinya tidak tahu apa motif
mereka datang ke tempat ini. Mereka semua berpakaian rapih dengan kemeja putih
dibalut dengan blazer dengan warna sama dengan warna mobil yang baru saja
mereka tumpangi. Celana panjang untuk para pria dan rok span selutut untuk si
wanita, serta tidak lupa sepatu yang licin dan mengkilap membuat tampilan
formal mereka sempurna. Di kepala mereka terdapat mahkota berupa topi berwarna
putih untuk salah satu pria dan sisanya memakai yang berwarna kuning. Mereka
mulai menggerakkan kaki-kaki mereka, melangkah ke arah barat daya. Berbeda
dengan tiga orang lainnya yang berjalan dengan tangan kosong, si wanita di
tangannya menenteng sebuah map berwarna biru. Setelah beberapa puluh langkah
dari mobil, si wanita membuka map biru yang entah isinya apa. Mungkin struk
daftar belanja mereka saat melipir ke minimarket pagi tadi. Mungkin juga
klasemen liga inggris pekan ini. Mungkin juga cerita pendek atau puisi romantis
dari penulis terkenal. Atau mungkin potongan berita utama di halaman pertama
koran hari ini yang membahas pembantaian kepada para kolegaku. Tidak tahu
pasti, tapi aku berharap dugaanku terakhirlah yang benar-benar ada di dalam map
biru.
Gedung-gedung
menjulang tinggi di sebelah barat, timur, dan selatan. Sedangkan di sebelah
utara terdapat jalan besar yang setiap harinya kendaraan berlalu-lalang di sana.
Sementara si wanita membuka dan memegangi map biru agar tidak jatuh, kedua pria
bertopi kuning secara bergantian berbicara, sepertinya menerangkan sesuatu
kepada pria bertopi putih. Salah satu pria bertopi kuning menunjuk map biru
yang terbuka untuk selanjutnya dia menunjuk ke tanah lapang di bagian barat
daya. Pria bertopi putih sesekali mengangguk mendengar penjelasan yang dia
dapatkan, seakan seperti seorang siswa kelas satu SD yang baru mengerti bahwa
satu tambah satu sama dengan dua setelah dijelaskan oleh gurunya. Aku sama
sekali tidak bisa mendengar pembicaraan mereka, entah karena jarak mereka yang
terlalu jauh denganku atau suara mereka terlalu kecil seperti halnya orang yang
berbicara saat sedang berada di tengah peperangan, suaranya kecil karena tidak
ingin diketahui keberadaannya oleh pihak musuh.
Pintu
mobil yang lebih besar dari mobil hitam mulai terbuka. Empat pasang kaki
lagi-lagi turun, sekali lagi berhasil mengalihkan perhatianku. Kini aku sudah
tidak tertarik lagi dengan apa yang empat orang berpakaian formal itu
bincangkan. Fokusku memperhatikan empat orang yang baru saja turun dari mobil
dengan seksama. Semuanya jantan. Berbeda dengan empat orang berpakaian formal
tadi, keempat orang ini gaya berpakaiannya lebih sederhana. Walaupun begitu,
keempat orang ini memakai topi yang sama dengan keempat orang berpakaian formal
tadi, kali ini semuanya warna kuning. Berbeda dengan empat orang berpakaian
formal tadi yang memang wajah mereka masih asing dalam ingatanku, keempat orang
ini memiliki perawakan yang tidak asing untukku.
Ingatanku tentang mereka mulai tergapai. Mereka salah
empat dari puluhan orang yang melakukan pembantaian terhadap para kolegaku.
Dari kejauhan, pria paling gemuk di antara keempat orang itu mulai mengacungkan
telunjuknya, menunjuk ke arahku dan satu kawanku. Aku takut mereka akan membuat
nasibku atau nasib satu kawanku atau nasib kami seperti nasib para kolega kami
yang lain. Salah dua dari empat orang, tidak termasuk si gemuk, pergi ke
belakang mobil mereka lalu dengan kecepatan kilat mereka sudah berdiri kembali
bersama gerombolan mereka, kali ini sudah bersama senjata yang mereka jinjing.
Setelah melihat senjata yang mereka bawa, diriku makin yakin mereka datang
dengan tujuan membunuh. Perlahan namun pasti mereka mulai mendekat selangkah
demi selangkah dengan sepatu-sepatu mereka yang kusam dan terdapat banyak tanah
kering yang melekat di permukaan luarnya. Mereka melangkahkan kaki ke arah kami
dengan wajah datar dan tidak merasa berdosa seperti psikopat. Makin lama mereka
makin dekat, sangat dekat, amat sangat dekat.
Mereka
sudah berjarak satu jengkal denganku dan satu kawanku. Ingin rasanya teriak
meminta pertolongan, tapi sayangnya tidak mungkin. Si gendut menempelkan
telapak tangannya ke tubuh kawanku. Hal yang sama juga dilakukan sebelum
membunuh para kolegaku. Kawanku menatap lemas, ketakutan terpampang di sekujur
tubuhnya. Bagi anda yang tidak mau melihat adegan sensitif silahkan untuk tidak
melanjutkan membaca cerita ini. Si gendut mulai mangkir dari posisinya,
sementara tiga orang lainnya mendekati kawanku. Masing-masing mereka mulai
mengangkat tinggi-tinggi senjata mereka yang berupa gerjaji mesin. Cara
pembunuhan yang cukup sadis mengingat mereka tidak menggunakan senjata tajam
seperti pisau atau golok seperti pembunuhan biasanya.
Tiga buah mesin bergigi banyak dan tajam mulai mereka
nyalakan. Terakhir kali aku melihat kawanku ini ketakutan adalah ketika ada
burung gagak hitam mengitari kepalanya dan hari ini aku melihatnya sekali lagi
dan ketakutan kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Kawanku bahkan tidak
mampu menatap para calon pembunuhnya. Tiga gerjaji mesin mulai menusuk-nusuk
tubuhnya. Kawanku menjerit sangat kencang dalam rangka merasakan sakit yang
begitu luar biasa. Semakin lama semakin dalam senjata itu merobek dan membelah
organ-organ di dalam tubuhnya. Jeritannya makin menjadi. Lama-lama aku tidak
sanggup menyaksikan kejadian itu lalu akhirnya memutuskan untuk tidak
melihatnya lagi. Seiring waktu jeritannya makin menipis. Suaranya secara
konsisten menurun sampai pada akhirnya hilang.
Bangkai kawanku yang sudah tergeletak di tanah. Melihatnya
terbaring tanpa nyawa membuatku menangis dan mengerang sekencang yang dibisa.
Aku merasa hancur sehancur-hancurnya melihat kawanku ini terbunuh. Bagaimana
tidak, sejak kecil kami sudah tumbuh bersama. Bertahun-tahun sudah melewati
hari-hari indah bersama. Terik dan hujan, kami menjalaninya bersama di sini, di
tanah lapang ini. Detik ini tidak ada yang bisa dilakukan selain menangisi
kepergiannya. Selagi ku merayakan kesedihan, si gendut memegang tubuhku dengan
tangan kasarnya.
Aku berdiri di tengah tanah lapang dengan matahari nangkring di atas kepala dan rasa tidak percaya bahwasanya aku akan tamat hari ini. Ada rasa ingin melawan mereka entah dengan memukul, menendang, atau serangan lain yang bisa membuatku bertahan dan mereka akhirnya tidak jadi membunuhku karena mereka babak belur dan terkapar lemas. Tapi hal itu tidak bisa dilakoni. Ada rasa ingin kabur dari sini dan lari secepat kilat untuk setidaknya menghilang dari pandangan mereka. Tapi hal itu juga tidak bisa kulakukan. Takut pasti ada, namun rasa takut itu kalah kuat dengan rasa pasrah akan nasib. Sampai detik ini aku tidak tahu apa tujuan mereka membunuh, tetapi satu hal yang aku paham betul, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Padahal aku dan para kolegaku yang secara perantara memberikan mereka kehidupan, atau setidaknya kaum mereka. Padahal aku dan para kolegaku yang-


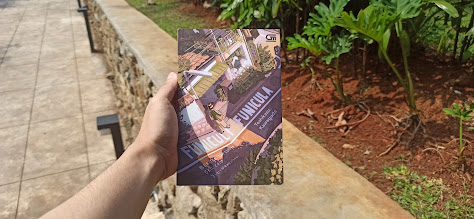

Komentar
Posting Komentar