Maukah Kamu?
“Maukah kamu… menjadi istriku?” katanya seraya mengeluarkan sebuah cincin dari saku celana lantas menyodorkannya ke gadis yang duduk di sampingnya.
Akhirnya Iwan mengutarakannya pada Rinda. Dia merasa bak pangeran yang akan melamar tuan puteri layaknya di film animasi romantis begitu selesai mengucap pertanyaan yang lebih kedengaran seperti permintaan itu. Tidak ada reaksi yang “wah” dari Rinda, gadis berponi jarang-jarang itu hanya tersenyum tipis. Tapi bukan berarti dia biasa saja atau bahkan kurang senang. Dalam hatinya jelas berbunga-bunga dan bersemangat. Tapi memang dasarnya dia tidak ekspresif, segala respon yang keluar pun seadanya. Iwan tahu soal itu dan tidak masalah sama sekali.
Rinda mengambil cincin lantas memakainya di jari manis tangan kanan. Dilihatnya cincin yang sudah melingkar itu berkilauan, seolah ada batu mutiara di atasnya. Sebetulnya Iwan agak heran mengapa Rinda memasangnya di jari manis dan ragu kalau itu posisi yang benar. Tapi dia memilih abai.
“Kalo begitu artinya mau, kan?” tanya Iwan meminta konfirmasi.
Rinda mengangguk. Lagi-lagi sambil tersenyum tipis.
“Di dunia ini banyak laki-laki yang lebih sempurna daripada aku. Kecantikan kamu bikin mereka berbondong-bondong datang nyoba melamar kamu. Tapi justru kamu lebih memilih aku yang masih banyak kekurangan sana-sini. Untuk itu… Makasih, ya.”
“Memang banyak yang mau melamar aku,” Rinda menatap Iwan penuh makna, “Tapi, aku cuma sayang sama kamu.”
Iwan memegang lembut kedua tangan Rinda sambil tersenyum, “Aku juga cuma sayang ke kamu.”
Untuk beberapa saat keduanya hanya diam. Hanya dedaunan di pohon-pohon dan poni Rinda yang bergerak tertiup angin. Kemudian tiba-tiba Iwan melepas genggamannya. Senyum hilang dari wajahnya. Dahinya mengerut menandakan ia sedang berpikir keras akan sesuatu. Rinda jelas heran.
“Tapi aku bingung, deh,” Iwan menggaruk-garuk kepala.
“Bingung kenapa?”
“Kamu bisa masak?”
Rinda menggeleng.
“Nah, sama. Aku juga nggak bisa buat tenda. Nanti pas acara nikahan gimana? Bisa-bisa nggak jadi nikah nih kita.”
Rinda tertawa kecil. Gantian Iwan yang heran.
“Kenapa ketawa?”
“Kita kan bisa pesen makanan ke katering. Tenda tinggal pesen ke penyewaan.”
“Katering?”
“Tukang masak buat acara pernikahan gitu.”
Mulut Iwan membulat, “Jadi kalo nikahan gitu nggak perlu kita sendiri yang siapin semuanya?”
“Ya nggak, lah. Tinggal pesen. Terus bayar, deh.”
“Mahal nggak?”
Rinda mengedikkan bahu.
“Berarti kita kumpulin uang dulu, baru habis itu nikah ya.”
Rinda mengangguk. Seperti biasa, lengkap dengan senyum tipis manisnya.
“RINDA… RINDA, AYO PULANG. MANDI,” ucap ibu Rinda dari kejauhan dengan sedikit berteriak.
Wanita berumur tiga puluhan awal itu berlalu masuk ke taman melewati jalan setapak untuk kemudian sampai di bangku yang diduduki anaknya dan Iwan.
“Iwan, Rindanya pulang dulu, ya. Udah sore soalnya.”
Iwan mengangguk ramah, “Iya, Tante.”
“Kamu juga langsung pulang. Takut ibumu nyariin.”
“Iya.”
Tubuh mungil Rinda beranjak dari duduk seraya mencopot cincin plastik merah berhiaskan buah stroberi di atasnya lalu mengembalikannya ke Iwan.
“Buat kamu aja. Aku ngapain simpen gituan.”
“Serius” Rinda memandangi cincin itu sekilas, “Makasih, ya.”
Ibu Rinda tersenyum tipis.
Begitu beres mengucap kata-kata perpisahan, Rinda berjalan menjauh mengikuti ibunya yang terlebih dulu berlalu. Iwan sedikit menyesali drama-dramaan ini selesai begitu cepat. Tapi mau bagaimana lagi.
Matahari masih belum mau tenggelam dalam waktu dekat. Iwan pun enggan pulang lalu memutuskan pergi ke lapangan di dekat masjid. Biasanya sore hari begini ada beberapa teman-teman sekelasnya di SD Nusa Bangsa. Iwan berniat ikut bermain bersama mereka.


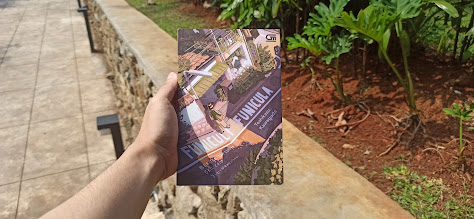

Komentar
Posting Komentar