Realita
***
“Nggak nyangka ya, kita udah nikah,” ucap Alam dengan masih menatap lurus kepada kawanan burung pingai yang sedari tadi mengitari tempat ini.
“Iya,” balas Sintia sembari tersenyum canggung.
Wanita yang mengenakan blus berwarna krem dan celana cutbray marun itu tidak tahu harus merespon apa soal perkataan Alam barusan. Serupa layaknya Alam, dia bercakap dengan tidak menatap ke lawan bicara. Berlainan dari alam, dia bercakap dengan menatap ke barisan bunga di arah timur laut yang menari sebab tertiup angin. Tidak hanya berwarna kuning, ada pula bunga merah, ungu, dan putih di sana. Tidak sepatah katapun keluar dari mulut Alam setelahnya. Hanya ada hening lengkap dengan perasaan canggung antar keduanya. Saking heningnya, kicauan kawanan pingai membisingi pendengaran mereka. Kalaupun ada satu masa di mana kicauan tidak terdengar, itu terjadi ketika dua remaja perempuan dan satu wanita yang terlihat lebih tua berlari kecil melintasi hadapan mereka sambil berbincang.
“Kamu inget warung bakso doa ibu?” suara Alam memecah kesunyian.
Depot bakso doa ibu berada di suatu jalan gang sekitar sepuluh menit jalan kaki dari tempat Alam dan Sintia bersekolah. Depot itu digandrungi oleh para pelajar pada masanya. Bagaimana tidak, cita rasa yang dihadirkan sempurna dengan porsi luar biasa lengkap dengan harga yang bersahabat bagi siswa. Tidak heran jika waktu pulang sekolah tiba, depot itu penuh dengan pelanggan yang mayoritas berseragam sekolah. Termasuk Alam dan Sintia. Alam bisa dibilang kecanduan bakso doa ibu. Sementara Sintia berkomentar “biasa aja”. Satu-satunya alasan dia selalu mau diajak Alam makan di sana yaitu sebab sehabis makan mereka bisa membeli es krim di kedai yang letaknya persis di seberang depot doa ibu. Sintia lebih menggemari es krim itu ketimbang bakso.
Banyak kenangan antara Alam dan Sintia di depot doa ibu. Satu yang paling Alam ingat terjadi saat mereka duduk di kelas dua sekolah menengah atas tepatnya tiga hari sesudah ulang tahun ketujuh belas Sintia. Saat itu mereka sudah beberapa bulan menjalin hubungan. Di depot itu Alam menyerahkan kado berupa anting-anting yang dibelinya di toko perhiasan dekat pasar tradisional. Anting berlapis perak imitasi itu memiliki berlian biru tua yang imitasi pula. Sintia terlihat senang begitu menerimanya. Dia lantas memakainya di tempat. Begitu beres menguncir kuda rambut, dia memiringkan wajahnya ke kanan lalu kiri. Kilau anting-anting masuk ke mata Alam.
“Cakep kan?” tanya Sintia meminta validasi.
Alam menyedot es teh manis yang tinggal setengah, “Cakep. Kamunya juga.”
Sintia hanya tersenyum manis. Pipinya memerah.
Alam menatap Sintia dengan senyum lembut, “I love you, Tia.”
“Love you too. Makasih ya kadonya, aku suka.”
Mereka menghabiskan sebagian besar masa remaja dengan saling memadu kasih dalam hubungan cinta monyet. Keduanya sangat bahagia dan bersyukur bisa mengasihi satu sama lain saat menghadapi masa muda yang merepotkan.
“Inget,” jawab Sintia singkat.
Tidak kunjung ada balasan dari Alam. Padahal dia yang sejak awal selalu memulai topik obrolan. Sintia menduga Alam sudah kehabisan topik. Karena tidak mau dianggap ketus, wanita itu memutuskan untuk bicara duluan.
“Masih sering ke sana juga?”
“Udah nggak. Warung baksonya kan udah bangkrut gara-gara kebakaran.”
Sintia menghadap ke wajah Alam untuk pertama kali, “Hah? Kebakaran? Kapan?”
“Mmm… Udah setahunan lah,” Alam balik menatap wajah Sintia, “Denger-denger bapak ibu itu sama anak-anaknya udah pulang ke kampung.”
Bapak ibu yang dimaksud yaitu pemilik depot bakso doa ibu. Sesudah itu Alam lanjut cerita bahwa sekarang depot itu telah berubah jadi tempat rental playstation. Sintia iba mengengarnya. Alam berkata kedai es krim yang ada di seberangnya juga sudah tutup permanen. Minat es krim yang terus menurun di daerah sekitar membuat pemiliknya coba masuk ke bisnis lain yaitu streetfood ala Korea.
Dulu Sintia selalu berbunga-bunga ketika membeli es krim di kedai itu sebab akan ada adegan romantis layaknya di film percintaan. Dia sengaja makan dengan belepotan agar Alam mengelap sekitaran mulutnya dengan lembut. Betapa bahagianya Sintia mendapat perhatian semacam itu dari pacarnya. Memasuki masa kuliah, Sintia sudah hampir tidak pernah mampir ke kedai itu. Meski begitu dia tetap dapat perhatian-perhatian manis dari Alam di kampus, seperti mengikatkan kembali ikatan sepatunya yang lepas, membantunya mengerjakan tugas sampai rela begadang, membelikannya makanan, dan sebagainya. Mereka sengaja masuk ke universitas yang sama agar bisa tetap berdekatan. Kian hari hubungan mereka makin serius.
Keduanya kembali senyap untuk kesekian kalinya. Sebetulnya Sintia ingin membuka topik lain, tapi bingung ingin membahas apa. Alhasil kicauan pingai kembali terdengar nyaring. Pikiran Sintia tiba-tiba saja pergi ke empat puluh lima menit lalu saat dia sedang duduk sendiri lalu ada sosok pria menghampirinya.
“Tia? Hai.”
“Eh? Oh, Hai,” balas Sintia sambil melambaikan tangan.
“Apa kabar? Sendirian aja?”
“Saya baik. Kamu sendiri gimana?”
“Alhamdulillah, baik.”
Pria itu menanyakan apakah bangku sebelah Sintia ada yang menempati atau tidak. Sesudah Sintia menjawab “tidak”, dengan canggung pria itu menanyakan apakah dia boleh duduk di situ atau tidak. Tidak ada alasan bagi Sintia untuk mengatakan “tidak boleh” mengingat taman ini adalah fasilitas umum. Siapapun boleh duduk di bangku yang tersedia. Dia tidak mungkin bicara “cari aja bangku lain yang masih kosong” sebab akan membuatnya terlihat congkak. Dia pun mempersilakan pria itu, juga dengan canggung.
“Masih sering ke sini?” tanya pria itu.
“Ng- Nggak juga.”
Mulut pria itu membulat mendengar kebohongan Sintia. Jelas-jelas Sintia masih sering ke sana untuk menenangkan pikiran kalut atau sekadar mengisi sore dengan santai. Sebab tidak ingin memberi kesan jutek Sintia balik bertanya walaupun tidak butuh jawabannya.
“Kalo kamu?”
“Jarang sih. Tapi ke depannya kayaknya bakal sering deh.”
Kalimat itu begitu membekas di pikiran Sintia. Dia mulai berpikir untuk tidak pergi ke taman ini lagi sebab tidak mau sering terjebak di situasi canggung nan kikuk seperti sekarang. Apalagi kalau sampai terlihat oleh seseorang yang dikenal, pasti akan muncul pertanyaan.
Ponsel Alam berdering. Dia beranjak dari bangku untuk pergi menjauh beberapa langkah lantas mengangkat panggilan masuk. Sementara Sintia kembali menatap barisan bunga, lebih tepatnya dua kupu-kupu yang mengitar di atasnya.
“Assalamualaikum. Udah? Udah selesai? Oke, ayah ke sana sekarang ya. Ke mana? Oh, yaudah. Simpen HP-nya di tas. Oke. Ya.”
Alam menutup telepon lalu kembali ke bangku lantas mengambil tas kecilnya. Dia harus segera menjemput Alfa, putra kecil Alam yang baru beres menjalani latihan di hari pertamanya di sekolah sepak bola yang jaraknya sepuluh menit naik sepeda motor dari taman ini.
”Sehat-sehat terus ya kamu sekeluarga,” ucap Alam sebelum pergi.
“Amin. Kamu sekeluarga juga sehat-sehat ya.”
Begitu Alam menghilang dari tempat ini, Sintia masih tetap duduk di sana sambil menatap kosong kepada barisan bunga yang tak lagi dihinggapi serangga. Dia mulai memegangi perutnya yang rata, wajahnya berubah sedih. Dua bulan lalu dia baru saja kehilangan janin berumur tiga bulan yang dikandungnya. Hal itu membuatnya sangat terpukul sebab dia sangat menantikan anak pertama itu. Dari perut dia beralih memegangi salib kecil di kalungnya seraya berdoa dalam hati agar dirinya dan suami dapat melewati semua ini dengan tabah. Hanya ada diam sesudahnya. Kicauan pingai masih terus menggerayangi telinga.


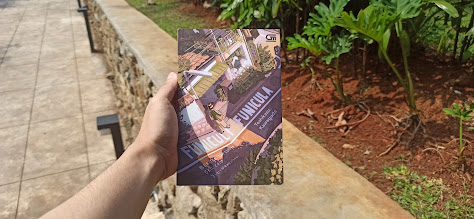

Komentar
Posting Komentar