[14DWC - Day 5] Impromptu
Ayah datang ke ruang tengah dengan tergesa-gesa saat aku, adikku, dan ibu sedang makan malam. Raut mukanya memberi tanda bahwa dia sedang panik. Ibu tidak jadi menyuap makanan ke mulut adikku dan melihat cemas ke ayah. Aku berhenti mengunyah makanan di mulut lalu ikut meneleng ke ayah. Tapi tidak dengan tatapan kayak ibu.
“Kita harus pergi dari sini sekarang,” kata ayah dengan nada tegas.
Ibu terperanjat, “Sekarang?”
“Di sini sudah tidak aman lagi,” jelas ayah, “Tadi ayah dapat kabar dari Doni kalau huru-haranya baru saja memasuki pintu gerbang desa kita! Bisa-bisa pas larut malam nanti akan sampai di rumah ini!”
“Huru-hara itu apa?” tanya adik dengan suara cemprengnya.
Kusenggol lengan adikku lalu meletakkan telunjuk di depan bibirku sambil mendesis. Aku sangat penasaran dengan cerita ayah dan aku tidak mau Fino mengganggunya. Sementara itu ibu hanya diam sambil melihat sepiring nasi berserta lauk yang sedang kami bertiga (aku, adik, ibu) makan. Benar, makanan satu porsi dimakan oleh tiga orang. Sudah tiga hari kami makan kayak begini. Sudah tiga hari juga sekolahku diliburkan padahal bukan hari minggu. Semuanya gara-gara satu sebab yang sama. Saat kutanya ke ibu soal apa yang menjadi sebab, ibu hanya menjelaskan bahwa diluar sedang bahaya.
“Doni sama anak istrinya sudah pergi dari sini saat matahari tenggelam. Keluarga Regas, Andra, dan Gondrong juga sudah pergi sebelumnya,” sambung ayah, “Kita tidak bisa terus-terusan di sini. Kita bisa terbunuh nanti!”
Terbunuh?
…
“Kita mau pergi ke mana, yah?” tanyaku penasaran.
“Ke rumah Bibi Tifa.”
Ibu dan ayah kelihatan sedang memasukkan baju-baju mereka, dompet berserta uangnya, dan obat-obatan ke dalam sebuah tas ransel dan sisanya ke tas plastik besar. Aku dan Fino juga diminta mengemas barang yang penting oleh ibu. Baju-baju termasuk seragam sekolah, buku-buku pelajaran, dan beberapa bungkus biskuit sudah masuk dalam ransel merah jambu. Sengaja kubawa kue gara-gara aku sudah tahu perjalanan akan lama. Sebab rumah bibi Tifa berada jauh di kota sebelah. Jaga-jaga kalau nanti lapar di jalan, jadi enak sudah ada persiapan.
Tas biru milik Fino sudah penuh tapi belum ditutup. Terlihat ada banyak sekali mainan robot di dalamnya. Fino protes padaku saat dia sadar semua robotnya kukeluarkan. Habisnya aku berpikir kalau pasukan robot itu bukan hal yang penting. Tapi dia tetap memaksa lalu mengadu pada ibu.
“Ya sudah, satu saja,” balas ibu.
Semua sudah dikemas rapi. Ibu mengunci semua pintu ruangan di rumah ini sedangkan ayah mengambil mobil bak dari parkiran lalu membawanya ke halaman belakang. Kami bertiga keluar lewat pintu belakang. Ibu bilang kalau mulai sekarang kami tidak boleh berbicara keras-keras. Fino mengangguk, tapi aku ragu dia akan menjalankan perintah ibu dengan baik. Sebab walaupun dia tidak bicara pakai nada keras tetap saja terdengar kuat gara-gara cempreng.
…
Mobil bergerak menembus jalanan lurus di tengah hutan yang dingin, sunyi, dan gelap. Tidak ada deretan lampu penerangan yang menyala di sepanjangnya. Saking gelapnya aku sampai tidak dapat melihat wajah ibu dan Fino dengan jelas di belakang sini.
“Ibu,” panggilku dengan nada berbisik.
“Kenapa?” jawab ibu dengan nada yang sama.
“Kita di rumah Bibi Tifa sampai kapan?”
“Tidak tahu, mungkin kita akan lama di sana.”
“Kalau minggu depan sekolah aku masuk bagaimana?”
“Tidak akan. Kamu masih akan lama lagi masuk sekolahnya. Kalaupun sekolah itu tidak kunjung dibuka untuk waktu yang sangat lama, lebih baik kamu pindah sekolah saja dekat rumah Bibi Tifa.”
Pindah sekolah?
Kalau benar-benar pindah ke sekolah baru, itu berarti aku akan meninggalkan teman-teman di sekolah lama. Aku tidak ingin berpisah dengan Lenni, Sisi, juga Gina. Mereka semua sangat baik padaku dan aku sangat menyayangi mereka. Membayangkannya saja aku tidak mampu, apalagi kalau benar-benar terjadi. Pikiranku kembali mengingat bangunan rumah, sekolah dasar, juga seluruh bagian desa yang baru saja kami tinggalkan. Kenapa kami semua harus pergi? Kenapa aku harus pergi? Aku ingin tinggal di sana. Aku ingin kembali ke sana.
Tiba-tiba mobil berhenti melaju. Terdengar bunyi pintu mobil dibuka. Cahaya dari lampu depan mobil membuatku dapat melihat jalanan di depan dengan lebih jelas. Tidak hanya jalanan yang sekarang terlihat, tapi batang pohon besar yang terbaring sehingga menghalangi jalan, lima orang laki-laki berbola mata hitam yang mengacungkan parang dan arit, juga ayah yang memegang parang di belakang tubuhnya sambil berdiri menghadap mereka. Aku langsung menjadi takut. Nenek Suna pernah bilang, benda tajam yang diacung-acungkan merupakan sebuah tanda akan datangnya malapetaka. Ibu guru di sekolah bilang kata malapetaka artinya bencana, sengsara, kesialan. Aku pernah belajar tentang bencana di mata pelajaran IPA dan dapat kusimpulkan bahwa bencana pasti menakutkan.
Ibu melarang aku dan Fino melihat ke depan sambil tangannya dengan cepat menutup mataku. Kayaknya mata Fino juga ditutup. Napas ibu terengah-engah.
“Kami mohon berilah kami selamat,” kata ibu dengan lirih dan kayak orang ingin menangis.
Ibu tidak menutup telingaku. Jadi aku masih bisa mendengar apa saja yang terjadi, termasuk di depan sana meski samar-samar. Ada beberapa potongan kalimat yang sempat terdengar. “Mata hijau,” “Salah,” “Munafik,” “Pergi,” “Lewat,” “Anjing,” “Mati,” “Bajingan,” “Saja,” dan “Pikirkan.” Tiba-tiba terdengar suara keras BUKKKK…. puluhan kali diiringi oleh lirihan dan tangisan ibu. Tidak tahu apa yang baru saja terjadi tapi itu membuatku takut.
Mataku terbuka. Terlihat ibu sedang mencari sesuatu dalam tasnya. Dia mengeluarkan sebuah parang. Persis kayak yang dipegang oleh ayah. Dia menurunkanku dan Fino dari bak belakang mobil lalu dia sendiri turun terakhir. Sepintas kulihat ke arah depan dan menemukan ayah tergeletak di tengah jalan dengan tubuh penuh dengan cairan merah.
Diriku ketakutan lalu menangis. Kungguncang-guncangkan tubuh ibu memakai kedua tanganku, “Bu, ayah berdarah banyak bu.”
“Sssst! Kamu jangan berisik. Sekarang kita lari ke dalam hutan sana!” dagu ibu menunjuk salah satu arah, “Kakak duluan, cepat!!!”
Diriku menuruti perintah ibu. Berlari sekencang mungkin menyusup di antara pohon-pohon tinggi dengan penerangan yang hampir tidak ada kecuali bulan di atas sana. Ibu menyusul dengan berlari sambil menggendong Fino yang sedang menangis. Terdengar salah satu dari lima orang tadi berteriak, “Mau kabur ke mana kalian? Akan kami buru sampai dapat lalu kami bunuh.”
Sepintas kulihat ke arah belakang dan menemukan lima orang laki-laki bertubuh tinggi itu sedang mengejar kami.
“Tolong, jangan bunuh kami,” teriak ibu sambil terus berlari, “Biarkan kami kabur.”
“Tidak akan!” suara berat membalas dari arah belakang, “Kalian suku berbola mata hijau sudah mencari gara-gara dengan suku kami!”
“Kami tidak ikut-ikutan. Kami hanya penduduk biasa yang hidup damai dan tidak tahu apa-apa soal konflik ini. Saya berani bersumpah.”
“Saya tidak peduli! Orang-orang suku anda sudah membunuh anak istri saya yang juga tidak tahu apa-apa. Sekarang giliran saya yang membunuh kalian!”
Diriku semakin ketakutan sehingga mempercepat lariku. Terus, terus masuk ke hutan yang lebih dalam, semakin dalam, terus lagi, dalam sekali. Saking cepatnya aku tidak sempat memperhatikan bongkahan batu yang membuatku tersandung. Benar, aku terjatuh lalu dengkulku terasa sangat sakit. Ibu mencoba membantu berdiri tapi rasanya aku tidak bisa bangun. Tiga suara berbeda terdengar olehku. Ringisanku sendiri, ibu yang tidak henti-hentinya menyuruhku cepat-cepat bangun, dan langkah para laki-laki tinggi itu yang semakin dekat.
Diriku takut. Aku tidak mau berada di sini. Aku ingin pulang ke rumah. Aku ingin makan biskuit sambil menonton acara televisi kegemaranku.
*****
One day this all will change.


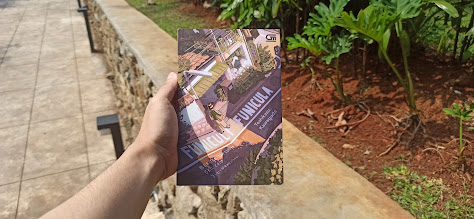

Komentar
Posting Komentar