Pemuda yang Ingin Menjadi Penulis
***
Bantalan busa pada kursi yang sekarang diduduki pemuda itu sudah koyak, membentuk lubang besar yang memperlihatkan permukaan kayu sebagai penopang bantalan kursi. Sementara rasa empuk kursi di kamarnya menghilang, pemuda itu tetap menempelkan pantatnya dengan nyaman dan bersikap seolah tidak ada kejanggalan apapun. Sama nyamannya sewaktu sekujur tubuh pemuda itu bermandikan angin dari mesin yang biasa disebut dengan kipas angin di tengah teriknya kota ini. Atau ketika pemuda itu beranjak ke kasur setelah seharian penuh berkehidupan. Atau dikala pemuda itu menenggak habis segelas penuh berisi teh hangat manis jambu, sebuah kegiatan repetitif yang dilakukannya setiap pagi, termasuk pagi tadi. Teh hangat manis jambu ditemani oleh beberapa buah tempe goreng tepung dan tahu goreng isi yang dibelinya di kedai nasi dekat rumah.
Pemuda itu hanya menyesap sedikit cairan bening coklat kemerahan yang ternyata masih terlampau panas untuk kemudian tangannya bergerak merogoh kantong plastik bening. Ada dua kebiasaan yang senantiasa pemuda itu lakukan sewaktu bersantap gorengan: Pertama, pemuda itu akan menyisakan tahu goreng isi untuk disantap terakhir sesuai dengan ungkapan save the best for the last. Kedua, pemuda itu akan memotong permukaan tepung yang menggumpal atau dianggap terlampau tebal untuknya lantas membuangnya. Berdasar pemikirannya, permukaan tepung yang semakin tebal akan membuat rasa tepung lebih dominan dibanding rasa santapan utamanya—seperti tempe, tahu, oncom, apapun. Peristiwa berikut tentu akan mengurangi kelezatan rasa dari keseluruhan gorengan. Adapun gorengan ternikmat yaitu gorengan yang rasa santapan utama dengan rasa tepung seimbang. Persetan dengan sensasi kriuk-kriuk yang mengasyikan.
Barisan gigi pemuda itu telah mendarat di permukaan tempe goreng tepung lantas digigitnya kuat-kuat hingga terbelah dua bagian. Pemuda itu mulai mengunyah bagian tempe yang hinggap di mulutnya. Tempenya padat, empuk, dan gurih, ditambah asin tepung yang terasa pas, lengkap dengan cairan minyak yang juicy. Remah-remahan kecil gorengan terjun bebas untuk kemudian mengotori meja atau lantai, tetapi pemuda itu tidak segera membereskannya. Antara tidak sadar atau mungkin tidak peduli. Pemuda itu menelan tempe ketika selesai melewati proses peleburan via mulut dengan wajah datar khasnya. Sekilas memang tidak ada yang berbeda dari pemuda itu pagi tadi. Tapi bila diperhatikan lebih jauh akan disadari bahwa tidak ada bunyi lain selain kunyahan gorengan, seruputan teh, serta lantunan suara monoton dan membosankan dari mesin yang biasa disebut kipas angin. Itu menandakan absennya lagu-lagu dari solois maupun band kontemporer yang biasa diputarnya. Itu menandakan suasana hatinya tidak seperti biasa—tenang dan santai. Supaya bisa tahu selengkapnya apa yang sedang terjadi dengan pemuda itu, mari kembali ke empat tahun sebelumnya.
Pemuda itu—seperti kebanyakan orang di dunia—punya satu kegiatan yang gemar diperbuat (baca: hobi) yaitu menyaksikan film dari layar gawai di kamarnya. Nyaris setiap harinya dijalani dengan menikmati suguhan berbagai cerita dari berbagai jenis genre. Beberapa di antaranya layak dinobatkan sebagai naskah film terbaik sepanjang masa, sebagian lainnya punya gagasan dan eksekusi brilian, ada pula yang punya potensi bila dikembangkan dengan lebih matang, serta sejumlah naskah yang lebih cocok berada di tong sampah dan sebaiknya tidak pernah difilmkan. Kategori terakhir paling diminati pemuda itu pada masanya sebab dapat memantik rasa percaya diri tinggi untuk turut menggubah naskah filmya sendiri. “Kalau cerita jelek begini saja ada produser dan sutradara yang mau jadikan film, berarti saya bisa jadi penulis film. Toh, saya bisa buat jauh lebih bagus daripada cerita ini,” ucap pemuda itu kepada dirinya sendiri di depan layar gawai yang sedang memutar film yang dianggapnya kurang bagus kalau tidak mau dibilang sampah.
Atas pemikiran demikian maka pemuda itu melakukan petualangan dalam pikirannya untuk menghadirkan garis besar keseluruhan cerita serta para tokoh lengkap dengan watak masing-masing (selanjutnya disebut rancangan naskah). Diucapkannya dalam hati sebuah kalimat penyulut semangat sebelum menulis huruf pertama pada halaman pertama, Saya akan menghasilkan karya dan dapat pengakuan sebagai seniman. Pengakuan yang diinginkan bukan dari orang sekitar atau bahkan masyarakat luas, tetapi dari pemuda itu sendiri. Lewat gerakan secepat kecepatan lari Usain Bolt jemarinya menari di atas keyboard. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman kesebelas, halaman ketujuh belas, halaman kedua puluh lima, halaman ketiga puluh tiga, halaman entah keberapa, halaman entah ke mana jalan ceritanya, halaman entah bagaimana ceritanya bisa putih bersih tanpa ada satu huruf pun tertuang.
Pikiran pemuda itu benar-benar buntu. Kata benar-benar perlu digarisbawahi. Benar-benar. Perbedaan pikiran buntu dan benar-benar buntu ada pada kebenarannya. Pikiran buntu—dalam konteks penulis—diartikan sebagai kondisi ketika penulis kehabisan ide sewaktu hendak memulai, melanjutkan, atau merevisi tulisan. Tetapi setelah mengambil jeda, menelisik inspirasi, dan minum jus mangga (opsional), penulis bisa dengan relatif lancar kembali memulai, melanjutkan, atau merevisi tulisannya. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa seorang penulis tidak benar-benar buntu. Sedangkan pikiran benar-benar buntu digambarkan dengan kondisi ketika penulis benar-benar kehabisan ide dan tidak bisa terisi kembali walau sudah rehat sejenak, melihat referensi, bahkan ketika sudah minum jus mangga. Pemuda itu tidak bisa apa-apa selain mengacak-acak rambutnya, memasang wajah kepingin menangis, dan meneriakkan beberapa kata kasar dalam bahasa Nepal.
Sebetulnya pemuda itu ingin berteriak kata kasar bahasa Indonesia. Tetapi urung diperbuat lantaran tidak ingin menarik perhatian orang sekitar untuk sibuk menasihatinya. Sebetulnya pun pemuda itu sudah menggubah gambaran detail cerita dari adegan pembuka sampai penutup. Tetapi di pertengahan jalan baru disadarinya ketidak masuk akalan pada beberapa bagian cerita. Beberapa kali sudah coba untuk diubah, tetapi tidak ada satupun hasil revisi yang seratus persen memuaskan idealismenya (baca: tidak ada satupun yang dianggapnya bagus). Itulah kekurangan pemuda itu: idealis tahap akut. Segala sesuatu harus bagus di matanya. Padahal pemuda itu tahu bahwa terkesan naif bila berpikir karya pertama akan bagus. Padahal pemuda itu tahu karya yang bagus bukanlah apa yang dianggapnya bagus, tetapi karya yang rampung dikerjakan. Tetapi tidak banyak berpengaruh sebab idealisme itu menggerogoti habis semangat menulisnya.
Rancangan naskah pertama dibiarkan mangkrak begitu saja seperti beberapa mega proyek di suatu wilayah antah berantah. Pemuda itu memikirkan ide cerita lain disusul dengan lahirnya rancangan naskah kedua. Dimulainya penulisan halaman pertama rancangan naskah kedua dengan semangat yang sama sewaktu memulai rancangan naskah sebelumnya dan berakhir dengan cara yang persis, sama, identik dengannya: mangkrak. Rancangan naskah ketiga pun demikian. Rancangan naskah keempat pun tidak kalah nahas. Pada akhirnya tidak ada rancangan naskah yang benar-benar menjadi sebuah naskah. Tetapi kekesalan pemuda itu terhadap keempat rancangan naskah yang berakhir tragis itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kegagalannya menuntaskan rancangan naskah kelima menjadi naskah utuh pertama.
Selama kurang lebih tiga tahun sejak pertama kali ide cerita rancangan naskah kelima muncul di kepala pemuda itu. Selama itu pula berkali-kali diusahakannya supaya rampung. Sempat dijumpai beberapa bagian cerita yang tidak semestinya berbentuk seperti adanya. Tetapi untuk rancangan ini pemuda itu bisa merevisi cerita dengan tetap memuaskan idealismenya. Alur cerita yang terlampau melenceng dari gagasan awal kembali diluruskan sebagaimana harusnya. Suatu karakter dengan sifat yang tidak sama pada awal dan akhir cerita diubah menjadi konsisten. Bagian naskah yang sudah rampung tetapi tidak serasi dengan bagian naskah berikutnya ditulis ulang supaya tetap tersambung. Sekilas rancangan naskah kelima ini akan dengan mudah dinaskahkan.
Namun kenyataan berkata lain. Walaupun sudah ratusan kali dibetulkan yang salah, ditambahkan yang kurang, serta diperbaiki yang rusak, tetap saja naskah yang belum rampung itu tidak pernah betul, tidak bertambah kualitas dan kuantitasnya, dan tidak lebih baik. Lubang cerita yang satu bisa diperbaiki, muncul lubang cerita yang lain. Lubang cerita lain bisa diperbaiki, muncul lubang cerita lain lagi. Begitu seterusnya. Belakangan pemuda itu baru menyadari rancangan naskah kelima terlampau kompleks untuk dikerjakan olehnya yang bahkan gagal merampungkan empat rancangan naskah simpel. Terlampau banyak konflik, karakter, serta bahasan yang ingin diangkat. Itulah ide cerita yang memuaskan idealisme pemuda itu: cerita rumit yang tidak mampu dirampungkannya. Dan seharusnya memang tidak perlu dikerjakannya.
Seseorang tidak mungkin bisa membuat dengan baik sesuatu yang rumit jika tidak bisa membuat yang simpel terlebih dulu. Pemuda itu mestinya lebih dulu merampungkan naskah dengan cerita yang lebih mudah seperti rancangan naskah pertama, kedua, ketiga, atau keempat sebelum naik ke tingkat yang lebih kompleks. Begitulah, nasi sudah menjadi bubur. Setelah pemuda itu sadar kapasitasnya sama sekali belum mampu merampungkan naskah dari rancangan naskah kelima, diputuskannya penghentian pengerjaan naskah itu sore kemarin. Perjuangan selama bertahun-tahun—terutama dalam sebulan terakhir—pun tidak lagi punya makna. Pemuda itu tidak bisa apa-apa selain mengacak-acak rambutnya, memasang wajah kepingin menangis, dan meneriakkan beberapa kata kasar, kali ini dalam bahasa Rusia.
Kenaifan akan idealisme melahirkan karya pertama yang bagus malah membuat pemuda itu masih gagal melahirkannya. Ironis memang. Cemoohan jelek, nggak bermutu, dan sampah yang dilontarkannya pada film kurang bagus yang disaksikannya tempo hari sekarang terasa lebih pantas disematkan untuknya. Kekesalan dan penyesalan tidak henti-henti menghuni pikiran dan perasaan pemuda itu bahkan hingga pagi tadi. Itulah mengapa lagu-lagu dari solois maupun band kontemporer tidak diputarnya ketika menyantap sarapan pagi tadi. Hari ini diniatkannya untuk melunturkan idealisme yang selama ini membuatnya susah sendiri. Akan dicobanya membuat karya yang relatif lebih mudah, mungkin akan rehat dari naskah film sejenak.
Sekarang pemuda itu duduk di depan layar monitor dan baru saja rampung menulis sebuah cerpen. Dianggapnya cerita itu jelek, tapi yang namanya karya pertama pasti banyak kekurangan sana sini. Di waktu yang bersamaan, dianggapnya cerita itu bagus sebab benar-benar rampung. Pemuda itu pun tersenyum puas. Bila penasaran dengan seberapa jeleknya cerpen yang dibuat pemuda itu, bisa dilihat dari penggalan paragraf pertama yang sedang terpampang di layar monitor: “Bantalan busa pada kursi yang sekarang diduduki pemuda itu sudah koyak, membentuk lubang besar yang memperlihatkan permukaan kayu sebagai penopang bantalan kursi. Sementara rasa empuk kursi di kamarnya menghilang, pemuda itu tetap menempelkan pantatnya dengan nyaman dan bersikap seolah tidak ada kejanggalan apapun….”


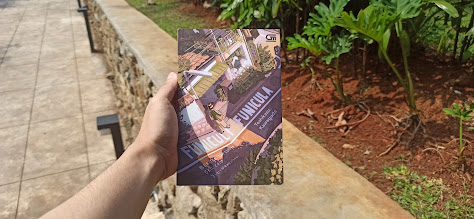

Komentar
Posting Komentar