Sudut Pandang
***
Setelah muterin hampir semua area taman, akhirnya ketemu juga bangku nggak berpenghuni yang gue cari-cari. Posisinya ada di salah satu sudut taman. Gue bisa lihat hampir semua orang yang ada di taman begitu duduk di sana. Ada sekumpulan remaja perempuan yang lagi piknik di atas rumput beralas kain bermotif gingham check, beberapa remaja perempuan lain duduk berdua dengan lawan jenis sambil mesra-mesraan, ibu-ibu muda asyik ngobrol, beberapa orang lain berlari kecil keliling taman, nikmatin indahnya berbagai jenis bunga, main ayunan, main lompat tali, baca buku, tapi yang paling narik perhatian gue yaitu anak-anak di tengah taman.
Gue tebak sih umurnya kisaran lima atau enam tahun. Mereka lagi main petak jongkok. Seru lihat mereka ngejar, ngehindar, ngegoda pengejar, dan ketawa lepas. Enak ya jadi anak kecil. Bisa ketawa selepas itu dan main sepuasnya. Nggak perlu mikirin kerjaan numpuk, ekspektasi, cicilan, tujuan hidup, rencana hidup. Tiap hari kerjaannya cuma makan, main, tidur terus dapat duit dari orang tua mereka. Meski nggak gede sih nominalnya.
Lagian, kan, anak kecil nggak butuh banyak juga. Buat apa coba.
Ngelihat sekumpulan bocah itu bikin gue flashback ke masa kecil gue puluhan tahun lalu. Badan kurus kering, pendek, sering dikatain “lidi patah” sama orang, tapi gue bahagia. Soalnya bisa main tiap hari tanpa mikirin apapun. Bisa tidur siang juga lagi—meski dulu gue paling susah disuruh boci. Beda banget sama gue versi sekarang yang tragis. Badan berisi, tinggi rata-rata, tapi nggak bisa main tiap hari, beban pikiran segunung, nggak pernah tidur siang. Boro-boro tidur siang, jam tidur malam aja sering kurang gara-gara lembur atau overthinking kenapa di umur menuju kepala tiga belum ada sesuatu yang bisa dibanggain.
Ditambah lagi harus ngadepin berbagai macam spesies klien resek tempo hari, sering dibujuk (dipaksa) orang tua buat jadi pegawai negeri dengan alasan hidup stabil dan hari tua terjamin meski anaknya satu ini nggak suka, gagal nikahin perempuan idaman setelah mergokin dia selingkuh seminggu sebelum akad, kena tipu puluhan juta sama rekan bisnis yang hilang jejaknya, terpaksa makan mie instan tiga kali sehari tiap akhir bulan, banyak kewajiban yang harus dibayar—sewa kamar indekos, cicilan mobil, premi asuransi, pajak.
Gue kepingin balik jadi anak kecil lagi, deh.
***
Xandreena dan kawan-kawan menyudahi permainan petak jongkok lalu menjatuhkan diri di atas rumput. Tak ada satupun dari mereka yang tak tampak kelelahan. Bulir-bulir keringat sebesar biji jagung mengalir deras dari tubuh mereka. Giovanni mengelapnya memakai handuk kecil yang sedari tadi digenggamnya. Gwen mengibas bagian depan kaus yang dikenakannya secara berulang. Sementara Aiden mengatur napasnya yang tersengal seraya telunjuk kirinya mencari harta karun di dalam hidung. Sekian lama mereka sibuk dengan dirinya masing-masing sehingga tercipta keheningan berkepanjangan sampai akhirnya Xandreena bersuara.
”Gwen, besok bawa lagi dong permen yang tadi. Enak banget, tahu.”
Gwen berubah lesu, ”Bunda aku nggak bolehin aku makan permen lagi soalnya udah kebanyakan. Baru bisa beli lagi katanya senin depan.”
“Senin depan itu masih lama?”
Gwen mengangguk dengan bibir cemberut. Xandreena kemudian bercerita bahwa sebetulnya dia juga mendapat larangan yang sama seperti Gwen dari mamanya. Bahkan mamanya tak menjanjikan hari di mana dia boleh membeli dan memakannya lagi layaknya bunda Gwen.
Xandreena mendesah, “Kenapa sih kita nggak boleh makan permen banyak-banyak.”
“Nggak cuma permen tahu, es krim juga,” sahut Gio.
Aiden menyentil jauh kotoran hidungnya, “Nugget juga.”
Gwen menyampaikan rencananya untuk membeli sendiri permen secara diam-diam. Tapi rencana itu langsung batal begitu tahu uang yang dipegangnya cuma seribu rupiah. Xandreena usul supaya mereka patungan untuk membelinya. Secercah harapan mulai terlihat di kejauhan. Dia mengeluarkan selembar dua ribu rupiah dan bertanya apakah tambahan darinya sudah cukup untuk membeli sekantong permen. Gwen menggeleng lalu memberi tahu bahwa harga permen sebesar tujuh ribu rupiah. Xandreena bertanya lagi—kali ini kepada Gio dan Aiden—apakah mereka punya uang. Dua-duanya kompak menjawab , “Nggak.”
Gio memasang wajah sebal, “Sedih ya jadi kita. Makanan yang kita suka dibatesin. Duit juga nggak punya.”
“Yang paling ngeselin tuh waktu main handphone juga dibatesin,” timpal Gwen.
Semuanya setuju ditandai anggukan kepala. Mereka saling berbagi penderitaan seputar itu. Mulai dari Aiden yang ponselnya ditarik paksa saat sedang seru-serunya bermain game online sampai Xandreena yang tiba-tiba diambil gawainya saat asyik menonton tayangan di Youtube.
“Enak ya jadi orang dewasa, bisa ngapain aja tanpa dibatesin dan dilarang-larang,” ujar Gwen, “Kakak sepupu aku bisa makan permen banyak-banyak.”
“Kakaknya temen sekolah aku juga katanya bisa makan dua belas nugget ayam sekali makan,” tambah Gio.
Aiden terkejut, “Banyak banget.”
“Iya, kan. Bahkan dia nggak pernah disuruh tidur siang kayak temen sekolah aku. Kayak kita. Padahal aku maunya main dari siang biar bisa lama.”
“Orang gede mah duitnya banyak. Udah gitu bebas pergi ke mana-mana sendirian, bisa dandan yang cantik kayak barbie,” ucap Xandreena tak menanggapi perkataan Gio.
“Bisa kelihatan keren juga pakai cara beli kopi mahal di kafe,” balas Gwen, “Aku malah nggak dikasih cobain kopi sama bunda aku.”
“Kata mama aku kopi nggak boleh diminum anak kecil,” jari Gio menunjuk satu persatu temannya lalu ditunjuknya ke diri sendiri.
“Kenapa?” Xandreena tampak penasaran.
Gio mengangkat kedua bahunya dengan wajah bingung.
Gwen menjulurkan kaki, “Pengen cepet-cepet jadi dewasa, deh.”
“Berapa lama lagi supaya kita jadi orang gede?” tanya Xandreena lagi.
“Masih lama kayaknya,” jawab Aiden dengan pasrah.
“Aduuuh,” Gio mengacak-acak rambut ikalnya tanda frustrasi.
“Biar cepet gede kita harus makan apa?” Xandreena menatap Gwen dengan penuh harapan, “Makan permen bisa nggak ya?”
“Nggak bisa sih kayaknya.”
Xandreena frustrasi seperti Gio. Tak lama kemudian sejumlah perempuan dewasa menghampiri mereka. Salah satu dari rombongan perempuan itu berdiri sambil mengulurkan tangan di depan tubuh Gio lantas menyuruhnya berdiri dan bergegas pulang ke rumah. Begitupun perempuan lainnya memegang buah hati mereka masing-masing. Di tengah perjalanan keluar area taman, Gio berbisik kepada Gwen.
“Satu lagi, orang gede bisa pulang malam.”
Gwen tersenyum miris.
Xandreena mendongak untuk menatap ibunya, “Ma, biar cepet gede Ina harus makan apa?”
“Eh, kenapa Ina nanya gitu?”
“Aku capek jadi anak kecil terus,” katanya semangat, “Mau jadi orang gede aja.”
Keempat perempuan dewasa itu kompak mengeluarkan tawa.
Ibu Xandreena mencubit gemas pipi sang anak, “Kamu ini ada-ada aja.”
***
Anak-anak itu pergi ninggalin taman ini bareng, boleh jadi, ibu mereka masing-masing. Wajar, sih, soalnya matahari dikit lagi bakal tenggelam. Pengunjung lain juga satu demi satu udah bubar jalan. Meski begitu gue nggak kepingin pergi dari sini sekarang. Buat apa pulang sekarang? Biar bisa istirahat? Apa gunanya balikin energi kalo nggak ada hari besok? Pokoknya gue tetep stay di sini, nggak tahu sampai kapan. Mungkin lima menit lagi, mungkin satu jam lagi, mungkin sampai sekitaran jam sepuluh malam, jam-jam di mana ibu gue mesti nelpon buat ngehasut gue ikut tes CPNS. Tapi sebelum sampai ke bahasan utama itu pertama-tama beliau bakal nanya.
“Gimana hari ini, Gus? Lancar?”
Pasti gue jawab, “baik-baik, kok, kayak biasa.”
Nggak mungkin, dong, ngasih kabar gue diberhentiin dari kantor pagi tadi. Pertimbangan gue ada dua urusan ini. Pertama, nggak kepingin makin dicecar buat ikut seleksi CPNS (ini udah jelas). Kedua, jangan sampai ibu bapak sedih gara-gara anaknya hlang pekerjaan. Ginilah, hidup gue sekarang. Harus banyak pura-pura.
Gue beneran pingin balik jadi anak kecil.
.gif)

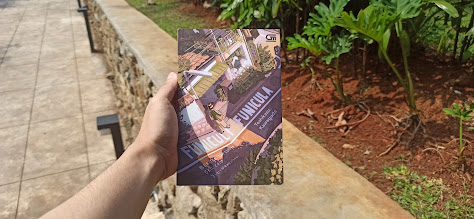

Komentar
Posting Komentar